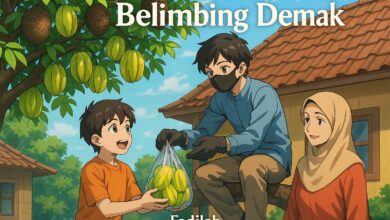Nyanyian Angsa
Raja Adiprana, yang dulunya memerintah Kerajaan Kartanegara, menarik jubah kasar yang kini membungkus tubuhnya. Gatal di pundaknya begitu mengganggu, tapi ia harus menahan diri agar tidak menggaruk dengan terang-terangan. Begitu ia menghela napas, sang pemimpin biara meliriknya tajam. Adiprana segera menundukkan kepala, menatap tanah berdebu yang mengotori kakinya yang dulu selalu beralaskan sutra.
“Tenanglah, anakku,” ujar pemimpin biara. Kini Adiprana bukan lagi seorang raja, melainkan seorang calon pertapa di Biara Angin Sunyi. “Waktumu akan tiba. Sementara itu, hiburlah dirimu dengan meresapi nyanyian suci angsa putih.”
Seolah mengerti, seekor angsa di kolam dekat sana mengeluarkan suara melengking yang menyusup hingga ke tulang. Adiprana menggigil. Entah mengapa burung-burung itu begitu dipuja di tempat ini. Kolam-kolam untuk mereka tersebar di seluruh penjuru biara, dan suara mereka tak pernah berhenti—siang dan malam, ha-hong ha-hong HOOONG!
Dan mereka benar-benar menyebalkan. Adiprana merapatkan jemarinya, teringat saat ia bertugas memberi makan mereka. Salah satu angsa sialan itu langsung menyerang, nyaris menggigit jari-jarinya. Roti yang ia bawa ludes, mangkuknya pun ikut hilang dibawa burung laknat itu.
“Bukankah itu sungguh menyenangkan?” tanya pemimpin biara dengan senyum bahagia.
Adiprana hanya mengangguk, menahan keinginan untuk mengeluh.
“Baiklah, kita akan melanjutkannya nanti. Sekarang, kau punya tamu yang menunggumu di pondok pengunjung.”
Adiprana hampir saja berlari menuju pondok itu. Di dalam, ia menemukan meja kayu sederhana dengan dua kursi reyot, teko tembaga tua, dan dua cangkir tanah liat yang penuh retakan. Dari jendela yang tanpa kaca, suara angsa masih menembus masuk, mengusik keheningan. Namun, lebih dari semua itu, yang paling penting adalah lelaki gagah yang duduk di hadapannya.
Raja Mahadipa, penguasa baru Kartanegara. Putra Adiprana sendiri.
“Yang Mulia,” pemimpin biara membungkuk dalam, mengulur waktu dengan formalitas yang tak perlu. Adiprana menahan geram, ingin cepat-cepat berbicara. “Seperti permintaan Anda, inilah Calon Pertapa Adiprana, yang kini dijuluki Saksi Angsa.”
Adiprana mengepalkan tangan di bawah meja. Begitu Mahadipa memberi isyarat halus, ia langsung duduk dengan cepat.
“Calon Pertapa,” pemimpin biara mengangkat lonceng perak kecil. “Saat lonceng ini berbunyi, sumpah bisumu akan ditangguhkan.”
Adiprana menahan napas, menunggu dengan tak sabar. Pemimpin biara mengangkat lonceng itu lebih tinggi… lalu lebih tinggi lagi… dengan gerakan yang makin lambat, hingga akhirnya bunyi nyaring yang amat kecil terdengar.
Adiprana mengembuskan napas lega.
Pemimpin biara tersenyum dan berkata, “Anda punya waktu satu jam. Setelah itu, Anda harus membersihkan patung para resi yang penuh kotoran burung.”
Begitu pemimpin biara pergi, Adiprana langsung memeluk putranya.
“Putraku!”
“Ayah! Sungguh senang bisa bertemu denganmu lagi!”
Mahadipa menepuk punggung ayahnya. “Sumpah bisu! Ayah benar-benar melakukannya! Aku kagum!”
“Ya… mereka melakukannya di sini,” jawab Adiprana canggung.
“Ayah, semua orang di Kartanegara begitu bangga padamu! Ayah yang telah menaklukkan wilayah-wilayah pemberontak, menyatukan para adipati yang tak pernah akur, lalu memilih untuk meninggalkan tahta demi mencari pencerahan!”
Adiprana tersenyum kaku. “Benarkah…”
“Orang-orang menyebut ayah seorang suci! Bahkan Paman Wirabumi dulu bilang ayah sudah gila! ‘Siapa orang waras yang meninggalkan kekayaan dan kemewahan demi bubur hambar dan kerja keras di pegunungan?’ katanya!”
Adiprana terkekeh hambar. “Ya… ya… aneh sekali, bukan?”
“Tapi aku tahu lebih baik! Ayah telah mencapai kebijaksanaan sejati! Sesuatu yang tak bisa kugapai! Aku terlalu lekat dengan duniawi—kenyamanan, kekuasaan… dan tentu saja, wanita!”
Adiprana memijat pelipisnya.
“Ayah, aku mungkin tak bisa sebijak ayah, tapi aku sangat bangga padamu! Keputusan ayah mengilhami seluruh negeri!”
Adiprana menelan ludah. “Bagus…”
“Omong-omong, benarkah para resi bisa mendengar suara dewa lewat nyanyian angsa?”
Di luar, seekor angsa meraung dengan suara seperti setan yang dicekik. Adiprana menggigil. “Y-ya… mereka sangat… inspiratif.”
“Tapi sudahlah, aku ingin tahu kabar ayah! Dan ayah pasti ingin tahu tentang kerajaan.”
Adiprana mengangguk semangat. “Benar! Bagaimana keadaan kerajaan? Aku khawatir…”
“Oh, ayah, jangan khawatir! Aku belajar dari yang terbaik!”
“Tapi seorang raja butuh penasihat…”
Mahadipa tertawa. “Penasihat? Aku punya banyak! Para tetua bijak dari segala penjuru datang untuk memberiku wejangan! Aku bahkan membentuk Dewan Raja, tempat para penguasa berkumpul demi membahas strategi bersama.”
Adiprana membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar.
“Dan ayah, aku punya rencana besar!”
“Ya?” Adiprana mencoba bersikap antusias.
“Aku berpikir untuk menghapus sistem kerajaan dan menggantinya dengan demokrasi!”
“TIDAK!” Adiprana hampir terjatuh dari kursinya. “Kenapa kau berpikir begitu!?”
“Entahlah, mungkin karena mahkota ini ternyata cukup berat… mungkin sistem ini tak adil…”
Adiprana merangkul bahu putranya erat-erat. “Dengar, Nak… Ada cara lain. Misalnya, kau bisa menyerahkan tahta kepada… seseorang yang lebih berpengalaman?”
Mahadipa mengernyit, berpikir dalam. “Hmm, maksud ayah… seseorang yang dekat denganku? Seseorang yang…”
Adiprana mengangguk berulang kali.
“Oh! Aku tahu! Seseorang seperti—”
Lonceng perak kembali berbunyi.
Kilatan pemahaman di mata Mahadipa lenyap.
“Waktu habis!” kata pemimpin biara.
Mahadipa mengerjapkan mata. “Apa yang tadi aku bilang? Ah, pasti tak penting. Senang bertemu ayah! Sampai jumpa tahun depan!”
Dengan lambaian jubah sutranya yang mewah, Mahadipa pergi.
Adiprana menatap kosong ke depan, sampai akhirnya pemimpin biara menyodorkan ember dan sikat ke tangannya.
“Waktunya membersihkan kotoran burung!” seru sang pemimpin. “Pencerahan datang lewat kerja keras, bukan?”
Adiprana menghela napas, berjalan melewati kolam dan taman, mengikuti jejak para resi terdahulu. Di kejauhan, terdengar seruan angsa yang seakan menertawakannya.